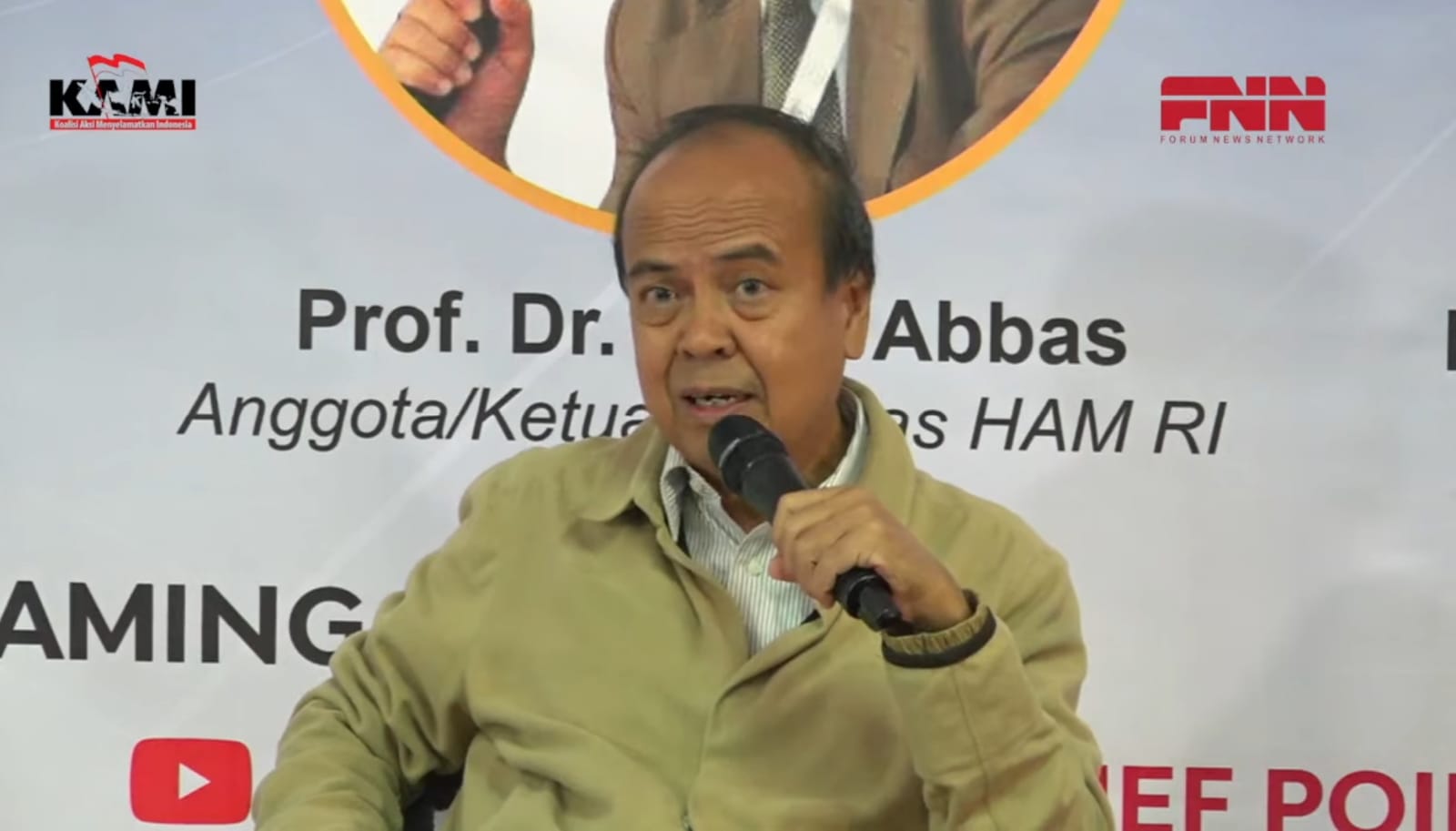Bentuknya sederhana. Dijaga tetap rapi dan bersih. Masih seperti aslinya. Rumah di Jalan Peneleh Gang VII nomor 29-31, Surabaya, sebagian ruangnya dulu pernah dijadikan oleh HOS Tjokroaminoto sebagai kos-kosan.
Di depan pagar kanan dan kiri pintu masuk, berjajar bunga tertanam di dalam pot. Bendera merah putih berdiri tegak dan berkibar tenang mengikuti hembusan angin sore.
Dinding bangunan yang tebal, tampak bersih dengan cat putih di semua bagian, dipadu warna cat hijau untuk daun pintu, kusen, dan semua jendela yang ada.
Di dekat pintu depan sebelah kanan, terdapat lempengan tembaga bertuliskan: Cagar Budaya, Rumah HOS Tjokroaminoto – SK Walikota No 188.45/251/402.1.04/1996 No Urut 55.
Sejuk dan nyaman. Ruang tamu yang melebar ke samping berukuran sekitar 10 kali 3 meter. Deretan pigura berjajar di seluruh ruangan. Foto dan gambar masa lalu, masa di zaman Hadji Oemar Said Tjokroaminoto menjadi bagian penting dalam gerakan politik perlawanan di masa kolonial Belanda, melalui Sarekat Islam.
Di sebelah kanan ada pintu, yang menghubungkan ruang tamu dan lorong ruang tengah. Ada pigura bergambar wajah HOS Tjokroaminoto dengan latar belakang Sarekat Islam.
Beberapa perabot kuno melengkapi ruang tamu, juga ruangan lain yang dulunya difungsikan menjadi kamar tidur. Di ruang tamu juga ada satu set meja kursi dari kayu jati, lemari kecil, atau oleh orang Surabaya biasa disebut sebagai laci.
Di belakang ruang tamu, berhadapan dua ruangan. Sebelah kanan atau di sebelah barat, dulunya dipakai untuk ruang kerja Tjokroaminoto, sedangkan di sebelah timur, kamar Sukarno. Kamar itu ditinggali setelah dia menikah dengan anak Tjokroaminoto, Siti Oetari.
Saat kos di sini, Sukarno tidak sendiri. Dia bersama rekan-rekannya. Mereka tinggal dan tidur di kamar atas, atau ruangan atas di lantai dua. Sementara kamar milik pemilik tempat kos, Tjokroaminoto, disket atau dibelah dua. Sebelah barat untuk ruang tamu, sebelah timur menjadi kamar Tjokro dan istri.
Berada di rumah ini, seolah masuk ke lorong waktu menuju era pergerakan nasional di Surabaya. Dari tempat itu, bisa dibayangkan bagaimana situasi saat kaum pergerakan melakukan aktivitas politiknya di kota ini. Diskusi dan rapat-rapat pergerakan, pendidikan politik dan membuat rancangan publikasi, menjadi aktivitas utama di rumah ini, pada masa lalu.
Satu Guru Beda Ilmu
Rumah HOS Tjokroaminoto, menjadi satu-satunya tempat paling bersejarah dalam pergerakan awal politik pribumi pada masa kolonial Hindia Belanda di Surabaya. Rumah ini hanya dihuni 10 orang, termasuk pemilik rumah dan anak kosnya. Kelak, para anak-anak kos inilah yang mewarnai sejarah Republik Indonesia.
Di rumah berpetak itu juga, Tjokroaminoto pernah disebut oleh pihak kolonial sebagai De Ongekroonde Van Java: Sang Raja Jawa Tanpa Mahkota.
Di rumah itu, Tjokroaminoto juga memberikan ilmunya kepada penghuni kos. Membangun pergerakan politik yang baru, dalam perlawanan terhadap kolonialisme.
Di rumah itu, Tjokroaminoto yang tidak memiliki penghasilan lain, memperoleh penghasilan sebagai pemilik kos-kosan, atas uang sewa sebesar 11 gulden, yang dibayarkan oleh setiap anak kosnya. Istri Tjokro, Soeharsikin, yang mengurus keuangannya.
Dari rumah itu pula, Tjokro kemudian menjadi pemimpin organisasi dengan jumlah anggota terbesar saat itu. Yaitu, Sarekat Islam (SI) yang anggotanya mencapai 2,5 juta orang.
Dari rumah itu juga, beberapa anak-anak kos, menjadi tokoh-tokoh penting dalam pergerakan dan dinamika sejarah Indonesia, sebelum atau sesudah kemerdekaan: Soekarno, Alimin, Moeso, SM Kartosoewirjo.
Di rumah yang sederhana itu, Tjokroaminoto bukan hanya sekadar menjadi bapak kos yang menerima uang sewa. Tapi juga, guru yang menggembleng wawasan berpikir penghuni kos —yang ketika itu masih berumur belasan tahun— menjadi lebih peduli terhadap nasib bangsanya.
Sosialisme digunakan sebagai pisau analisis dalam menyikapi penghisapan kapitalisme. Islam, dijadikan dasar dari perjuangan politiknya. Ditambah, saat itu semangat zaman untuk perubahan di dunia, mulai bergejolak.
Selain perjuangan melawan kapitalisme yang dilakukan oleh kaum sosialis dan komunis di Eropa, juga muncul kebangkitan gerakan Pan Islamisme yang digelorakan oleh Muhammad Abdul dan Djalaludin Al-Afghani. Selain itu, muncul juga gagasan civic nationalism oleh dr. Sun Yat Sen di Cina.
Menjadi Orang Besar
Semangat zaman itu terserap dalam diri Tjokroaminoto, yang tercermin dalam tulisannya yang berjudul “Islam dan Sosialisme”. Karena itulah, beberapa murid Tjokroaminoto, selain bergabung ke SI, juga ada yang bergabung ke Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang digagas oleh Henk Sneevliet pada 1914.
Persoalan muncul dan bmenjadi konflik yang pelik, saat Komunis Internasional (Komintern) tidak menerima Gerakan Pan Islamisme. SI pun terbelah. SI Merah, berkiblat ke komintern. Sementara, SI putih berkiblat ke Pan Islamisme.
Terjadi pula polemik antara Semaoen dari SI merah dan KH Agus Salim dari SI putih. Moeso yang berlatar-belakang pesantren, meskipun condong ke SI merah, namun tetap menghormati Tjokroaminoto, gurunya.
Tjokroaminoto memang pantas disegani. Di tangannya, SI yang semula beranggotakan 85 ribu anggota SDI saat Tjokro memulai kepemimpinannya, berkembang menjadi 2,5 juta pada tahun 1919.
Tjokroaminoto sangat dihormati, bukan saja oleh murid-muridnya, melainkan juga tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Termasuk dari kalangan Boedi Oetomo dan Indische Partij yang sama-sama berjuang mengangkat harkat-martabat kaum Bumiputera.
Inilah, yang kemudian membuat Raden Soekemi, seorang guru Eerste Inlandse School, Mojokerto, Jawa Timur, menitipkan anaknya, Sukarno yang masih berusia 15 tahun, untuk mondok di kos-kosan Tjokroaminoto.
Kala itu, Sukarno baru lulus sekolah Europe Lagere School (ELS) dan diterima sekolah di Hogere Burger School (HBS) Surabaya.
Keputusan Soekemi ternyata tepat, karena dari rumah kos-kosan di Jalan Paneleh Gang VII itu, kelak anaknya–bersama Muhammad Hatta–, tercatat sebagai Proklamator Kemerdekaan dan sekaligus Presiden pertama RI.
Kemampuan berpidatonya banyak diasah di Jalan Paneleh itu. Kelak, Sukarno juga dikenal sebagai orator ulung yang mampu menggetarkan Sidang Umum PBB.
Sukarno ingat betul kata-kata Tjokroaminoto. Bahwa, untuk menjadi orang hebat kuncinya adalah pandai menulis dan cakap berpidato. Sejak di kos-kosan itu, Sukarno yang masih pelajar setingkat SMA, sudah belajar pidato di muka cermin.
Kelakuan Sukarno sering kali dianggap mengganggu penghuni kos yang lain. Termasuk Moeso, Semaoen, Dharsono dan SM Kartosoewirjo.
Tapi Sukarno bersikap acuh. Di kamarnya yang gelap dan hanya diterangi lampu minyak, Sukarno tetap belajar pidato. Seorang sahabatnya yang tak pernah lelah mengkritiknya adalah SM Kartosoewirjo. “Kenapa pidato di depan cermin? Seperti orang gila saja,” kecam Kartosoewirjo.
Biasanya setelah usai berlatih pidato, barulah dia menanggapi dengan menirukan ucapan gurunya,“Kalau mau jadi orang besar harus pandai pidato, dan saya ingin menjadi orang besar. Tidak seperti kamu, jelek, hitam, mana mungkin jadi orang besar?”
Sukarno bersahabat dengan Kartosoewirjo, yang usianya masih seumuran dengan Sukarno. Kartosoewirjo sendiri masih keponakan Mas Marco Kartodikromo, tokoh jurnalis kiri.
Kartosoewirjo juga rajin membaca tulisan-tulisan pamannya yang beraliran sosialis. Seperti halnya Sukarno, Kartosoewirjo juga menganggap Tjokroaminoto sebagai panutan.
Sejak di Surabaya, selain bergaul dengan orang-orang SI, Sukarno justru ikut organisasi Tri Koro Dharmo yang dibentuk oleh Boedi Oetomo. Maka tidak mengherankan bila ide-ide nasionalisme lebih mengemuka dalam diri Sukarno. Terlebih setelah dia membaca San Minh Chu I karya Dr. Sun Yat Sen tentang Civic Nationalism, Democracy dan Kesejahteraan Rakyat.
Meski berada dalam satu wadah, satu guru, para penghuni kos itu kemudian lahir dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dari Semaoen, Alimin, Musso, Dharsono hingga Tan Malaka lahir pemikiran komunisme. Sementara dari SM Kartosoewirjo, lahir pemikiran Islam modern. Dari Sukarno lahir pemikiran nasionalis.
Perbedaan inilah yang kemudian menjadi persimpangan jalan antara Sukarno dan Kartosoewirjo kelak. Meskipun keduanya sama-sama mengaku sebagai murid politik Tjokroaminoto, namun Sukarno yang juga bergaul dengan Douwes Dekker dan Soewardi Soerjaningrat –yang keduanya adalah tokoh Indische Partij– tidak mengikuti jejak politik gurunya.
Bahkan, pada 4 Juli 1927 Sukarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Sebaliknya, Kartosoewirjo tetap setia mendampingi gurunya, Tjokroaminoto hingga tahun 1929.
Kelak, paska kemerdekaan, Kartosoewirjo yang juga turut berjuang dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, kecewa atas hasil perundingan Roem-Royen. Sejak itu Kartosoewirjo mengobarkan pemberontakan melalui Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan berhasil ditumpas Sukarno pada 1962.
SM Kartosoewirjo dihukum mati. Kabarnya, Sukarno sempat lebih dari 3 bulan tidak mau menandatangani eksekusi kematiannya. Persahabatannya dengan Kartosoewirjo di usia belasan tahun membuatnya berat hati.
Namun desakan penegakan hukum, membuat Sukarno sambil menangis terpaksa menandatangani eksekusi kematian sahabatnya. Itulah satu-satunya eksekusi mati yang pernah ditandatanganinya.(*)